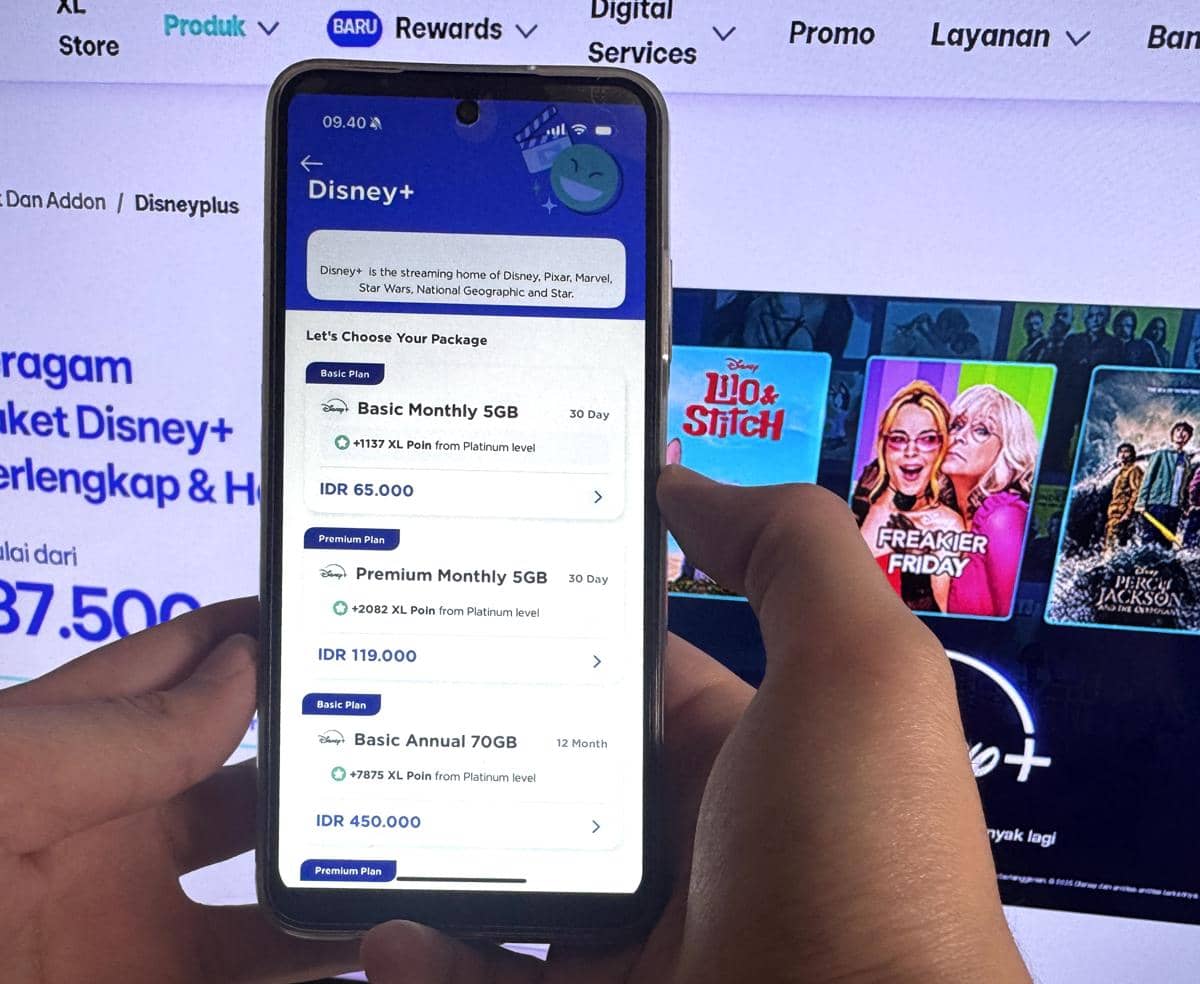Polemik Royalti Musik: Kuat Secara Hukum, Tapi Lemah Implementasi

- Transparansi distribusi royalti masih dipertanyakan
- Soroti kinerja LMKN dan pengawasan di daerah
- Dorong reformasi kebijakan royalti
Bandar Lampung, IDN Times – Persoalan penarikan royalti musik di Indonesia ramai dibahas di ruang publik. Sederet kasus melibatkan penyanyi kenamaan Tanah Air viral hingga timbul pro-kontra di masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung.
Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Benny Karya Limantara menilai, secara normatif aturan royalti sudah cukup kuat. Namun persoalan terbesar justru muncul pada tahap implementasi di lapangan.
“Secara normatif, aturan sudah jelas. Setiap pihak yang menggunakan musik secara komersial, baik itu restoran, hotel, kafe, karaoke, radio hingga platform digital, wajib membayar royalti. Jadi memang kepastian hukumnya sudah ada,” kata Benny, Jumat (29/8/2025).
1. Transparansi distribusi royalti masih acapkali dipertanyakan

Benny menjelaskan, ketentuan dasar hukum mengenai royalti telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.
Menurutnya, regulasi ini menempatkan royalti sebagai hak ekonomi yang melekat bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, ia menegaskan praktik di lapangan menunjukkan masih banyak masalah, salah satunya terkait transparansi distribusi royalti sering kali dipertanyakan oleh para musisi.
“Musisi kerap merasa tidak memperoleh hak yang proporsional. Di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil seperti kafe atau UMKM merasa terbebani karena tarif dianggap tidak sesuai kemampuan finansial mereka,” jelasnya.
Selain itu, mekanisme keberatan atau banding atas tarif juga belum diatur secara jelas. Alhasil, kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pihak-pihak yang dibebankan. "Ini terutama ketika tarif diberlakukan sama untuk usaha skala besar maupun kecil," lanjut dia.
2. Soroti kinerja LMKN dan pengawasan di daerah

Polemik royalti musik dinilai kerap berulang karena adanya asimetri informasi. Sebab, banyak pelaku usaha tidak memahami dengan baik perbedaan antara izin memutar musik dengan kewajiban membayar royalti.
“Di sisi lain, musisi tidak tahu berapa besar sebenarnya royalti yang dihimpun dan bagaimana pembagiannya. Kurangnya transparansi membuat kepercayaan publik menurun,” tegas Benny.
Di sisi lain, ia turut menyoroti lemahnya koordinasi antar pemegang kewenangan di pusat dengan daerah. Menurutnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bekerja di tingkat pusat, sementara pengawasan di daerah kerap tidak seragam.
“Ada daerah yang longgar demi mendukung UMKM, ada juga yang ketat mengikuti instruksi pusat. Inilah yang menimbulkan ketidakseragaman implementasi,” tambahnya.
3. Dorong reformasi kebijakan royalti

Menjawab persoalan tersebut, Benny mendorong adanya reformasi kebijakan royalti yang lebih modern, progresif dan berbasis digital. Sejumlah langkah kongkret dapat diterapkan para pembuat kebijakan, guna menuntaskan permasalahan tersebut.
Langkah ditawarkan antara lain digitalisasi penuh sistem royalti, penerapan skema tarif proporsional, integrasi pusat-daerah dalam pengawasan, edukasi hukum berkelanjutan, hingga pembentukan lembaga pengawas independen di luar LMKN.
“Royalti musik jangan hanya dipandang sebagai beban administratif, tapi bagian dari keadilan ekonomi kreatif. Reformasi digital, transparansi, dan keadilan tarif adalah kunci menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan pengguna,” tegas dia.
4. Ubah pendekatan represif jadi kolaboratif, adaptif dan berbasis teknologi

Benny menambahkan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius sekaligus mengubah pendekatan mengenai pembayaran royalti musik dari model represif menjadi kolaboratif, adaptif, dan berbasis teknologi.
Kalau itu dilakukan, royalti musik benar-benar bisa menjadi instrumen perlindungan hak cipta sekaligus penggerak ekonomi kreatif nasional,” kata Dosen Fakultas Hukum tersebut.