Mengapa Banyak Laki-Laki Menolak Membaca Buku Fiksi?

Menurut beberapa data global yang dihimpun Deloitte dari empat sumber berbeda pada 2021, pembaca buku didominasi perempuan, terutama di kategori fiksi. Ini didukung data Marketing Charts menemukan bahwa pembaca pria kebanyakan memilih buku nonfiksi
Alasannya cukup klise, salah satunya kesan buku fiksi tidak berfaedah layaknya buku nonfiksi. Lantas, apa yang mendasari kecenderungan laki-laki menolak membaca fiksi ini muncul? Adakah alasan psikologis dan saintifik yang bisa menjelaskan fenomena tersebut?
1. Anggapan membaca fiksi sama dengan membuang waktu

Alasan umum dipakai para penghindar fiksi adalah anggapan membaca buku-buku cerita (novel, komik, dan kumpulan cerpen) hanya buang waktu. Seperti kata Jason Diamond dari GQ, membaca fiksi tidak cocok dengan hustle culture (budaya gila kerja).
Ketika dunia bergerak cepat, terbentuklah pola pikir untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Buku, terutama kategori fiksi bukanlah salah satu yang layak masuk prioritas.
Hal ini digaungkan pula oleh para pemengaruh, terutama yang menganut aliran supremasi pria dan menggunakan persona hipermaskulin seperti Andrew Tate. Ia pernah menulis cuitan soal buku yang menurutnya hanya cocok untuk orang-orang yang menghindar dari realitas.
Mengingat masih banyak yang menganggap pria harus jadi provider alias pencari nafkah utama dalam rumah tangga, maka jelas fiksi yang dianggap tak berfaedah itu tidak layak menyita waktu mereka. Intinya, ada banyak hal lebih penting yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup di dunia yang kapitalis ini.
2. Nonfiksi terkesan mampu memberikan imbal balik lebih cepat dan terlihat
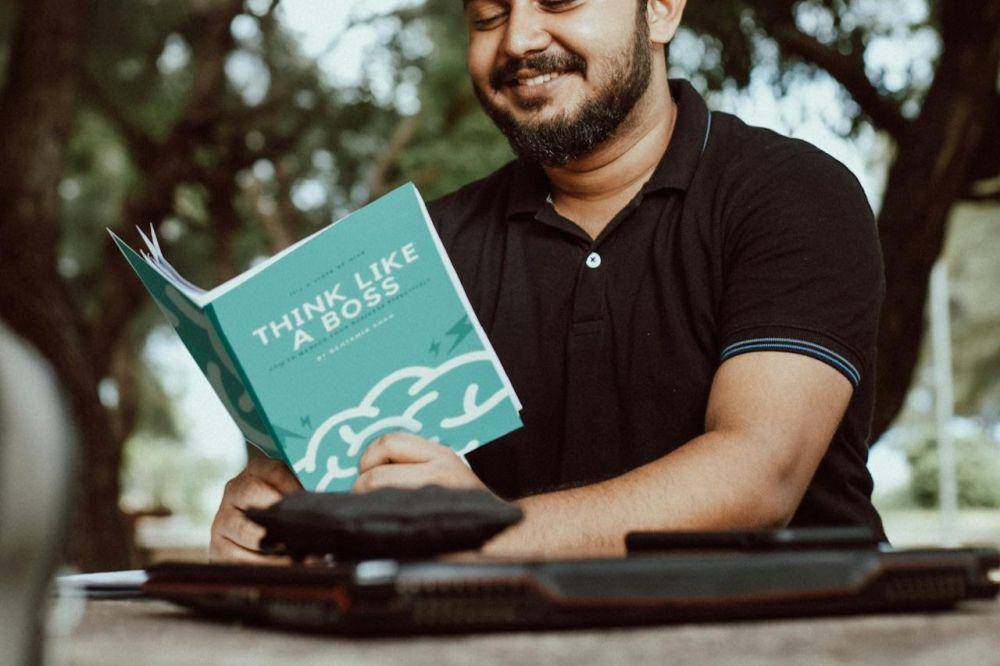
Kesan buang-buang waktu itu berkaitan erat dengan investasi waktu dan dana yang harus dialokasikan seseorang untuk menyelesaikan sebuah buku. Mengingat fiksi seringkali berupa cerita tanpa akurasi yang bisa dipertanggungjawabkan, orang dengan mentalitas seperti poin pertama akan lebih memprioritaskan buku nonfiksi.
Mengutip kalimat Dr Alistair Brown dari Durham University seperti dipublikasikan majalah Dazed, nonfiksi terkesan bisa memberi imbal balik yang lebih bermakna dan langsung dari investasi waktu yang sudah dikeluarkan seseorang.
Pesan dan pelajaran dari buku nonfiksi lebih cepat tertangkap dan masuk ke otak pembaca ketimbang fiksi yang lebih abstrak dan mungkin untuk sebagian orang terasa lebih berbelit. Apalagi untuk orang yang menerapkan metode skimming untuk menyelesaikan buku nonfiksi. Teknik tersebut akan susah dilakukan saat kita membaca novel atau fiksi.
3. Ide maskulinitas mainstream mempromosikan model pria tidak introspektif dan masa bodoh

Padahal, fiksi punya peran krusial dalam peradaban manusia. Fiksi sebenarnya juga kaya pengetahuan, tetapi dikemas dengan format cerita naratif yang terkesan seperti produk hiburan.
Genre fiksi sejarah dan realisme misalnya adalah buah riset dan observasi penulis yang bisa mendorong pembaca untuk menyusuri fakta sebenarnya. Fiksi juga diciptakan sebagai ruang untuk melakukan kontemplasi, tepatnya lewat penggambaran kehidupan yang jauh dari jangkauanmu serta perspektif yang mungkin belum pernah terbersit di benakmu.
Namun, ide maskulinitas mainstream cenderung tidak mempromosikan kebiasaan introspeksi dan berempati pada pria. Pria ideal dalam pandangan maskulinitas mainstream (cenderung toksik) adalah sosok yang tangguh, tidak mengandalkan emosi, dan logis. Ini yang akhirnya menciptakan kesan kalau buku fiksi tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pria.
Padahal, sebaliknya di tengah tekanan untuk jadi tangguh dan kuat di segala situasi, pria justru butuh fiksi untuk membantunya melatih kepekaan sosial dan melakukan introspeksi. Membaca buku sejarah dan self-help memang terasa lebih berharga, tetapi bila ingin memperkaya perspektif yang menapak tanah dan lekat dengan realitas, fiksi justru solusinya.














































