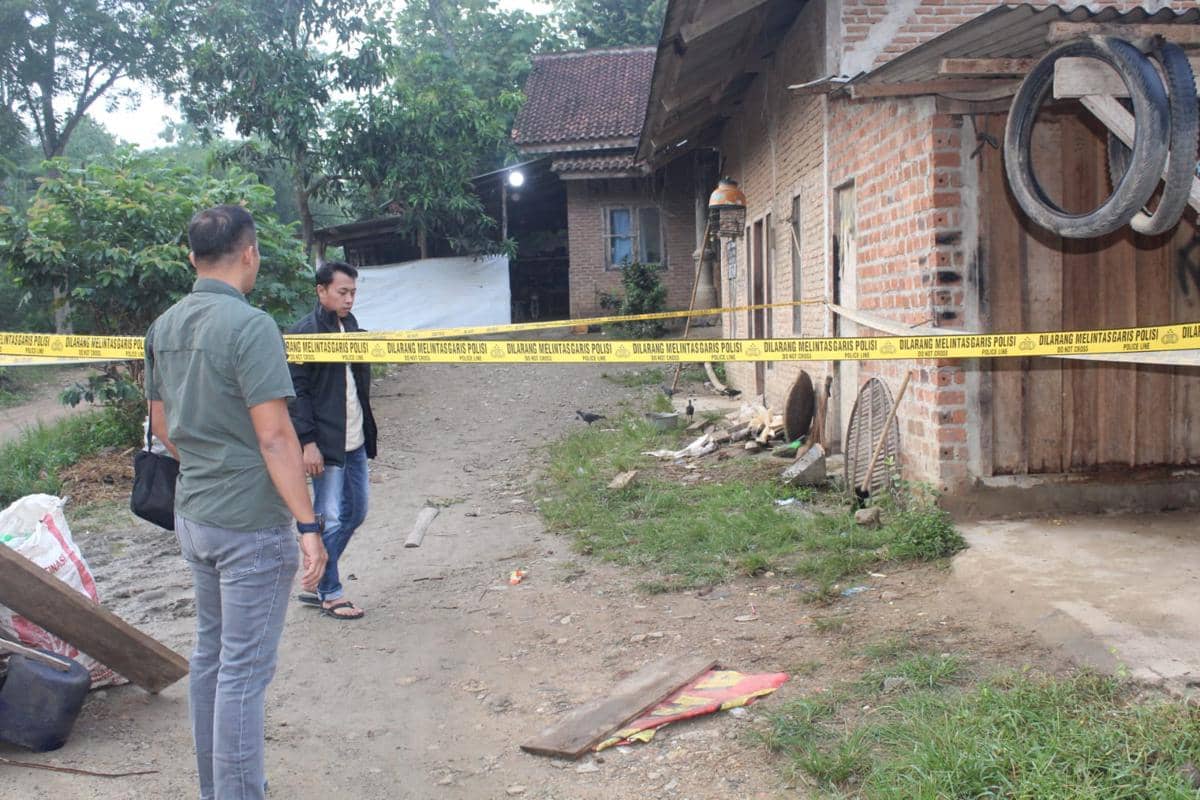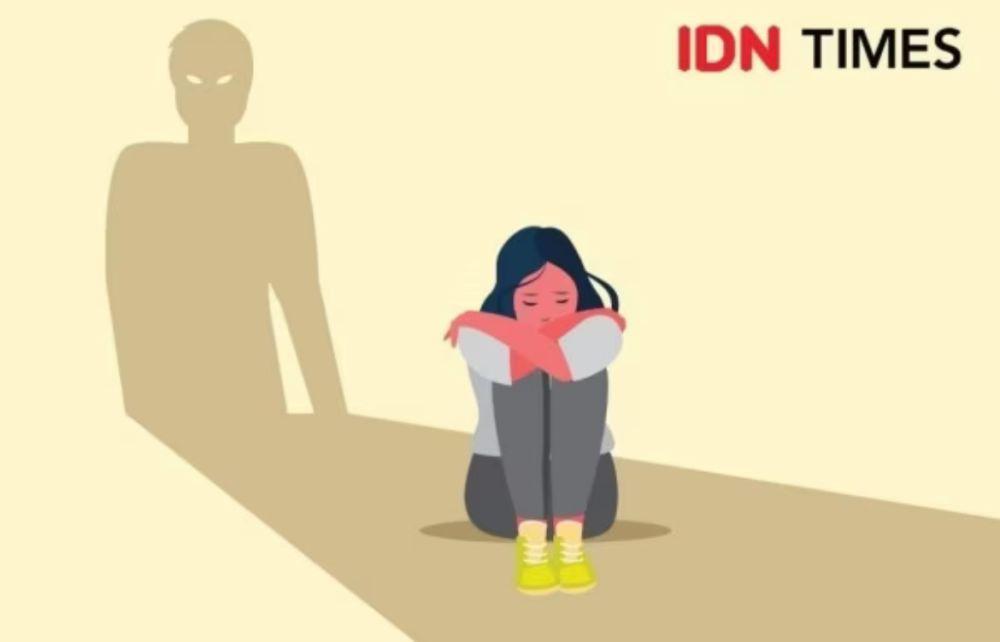Menakar Kemajuan Kota dari Permukiman

- Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencerminkan kemajuan kota, namun komponen seperti infrastruktur dasar dan lingkungan hidup belum sepenuhnya terakomodasi.
- Kota kecil Jepang berhasil menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperkuat infrastruktur permukiman terintegrasi dengan transportasi publik dan teknologi smart grid.
- Kota-kota di Indonesia perlu memperkuat kebijakan yang tidak hanya berhenti pada visi besar, tetapi juga disertai dengan petunjuk teknis yang detail dan implementatif sesuai kondisi di lapangan.
Beberapa waktu terakhir, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 yang dirilis oleh BRIN menjadi perbincangan hangat di ruang publik Provinsi Lampung. Kota Metro berada di posisi pertama, disusul Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu.
Ketiganya disebut sebagai daerah dengan daya saing tertinggi di provinsi. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek seperti institusi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ekosistem inovasi. Wajar jika banyak yang menilai daerah-daerah tersebut telah “maju”. Dan sebagai warga Kota Metro yang beraktivitas sehari-hari di Kota Bandar Lampung, tentunya informasi yang cukup viral ini sangat membanggakan, paling tidak pada awalnya.
Namun, dibalik euforia peringkat dan angka-angka indeks, muncul pertanyaan yang lebih mendasar, apakah ukuran tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa suatu kota benar-benar sudah layak huni dan berkeadilan bagi semua warganya? Atau dengan kata lain, apakah kota-kota tersebut sudah dapat disebut sebagai kota yang maju?
1. Filosofi sandang, pangan dan papan

Indeks Daya Saing Daerah memang komprehensif, tetapi komponen seperti infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup hanyalah sebagian kecil dari puluhan indikator yang dinilai. Padahal, realitasnya, yang paling dirasakan oleh masyarakat sehari-hari adalah akses ke air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta kondisi hunian dan permukiman. Jika indikator-indikator ini masih menyisakan banyak persoalan, maka capaian indeks yang tinggi bisa menutupi kenyataan yang belum selesai di lapangan.
Untuk memahami esensi “kemajuan”, kita bisa mengutip kembali filosofi yang mendasar sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini, papan, yang merujuk pada rumah dan lingkungan tempat tinggal, merupakan fondasi paling konkret. Kota yang disebut maju semestinya sudah memastikan seluruh warganya memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.
Jika kawasan permukimannya saja masih bermasalah, bagaimana mungkin kita menyebut kota itu telah berkembang? Dalam skala yang paling kecil, kita sebagai manusia pun sering kali dinilai oleh masyarakat baik atau tidaknya dilihat dari kondisi tempat tinggal kita. Rumah menjadi cerminan pemiliknya.
Laporan Voluntary Local Review (VLR) Kota Bandar Lampung 2022 menyebutkan proporsi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh masih cukup signifikan. Akses terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya merata. Di Metro, meskipun secara administratif tertib dan indeks daya saingnya tinggi, ruang interaksi sosial yang ramah anak dan lansia di kawasan permukiman masih sangat terbatas. Di Pringsewu, sistem drainase kawasan padat penduduk masih belum terpadu. Capaian administratif sering kali tidak berbanding lurus dengan kualitas lingkungan hidup di permukiman.
2. Kota kecil Jepang berhasil menerapkan prinsip keberlanjutan

Sebagai pembanding terhadap perspektif angka indeks agregat seperti IDSD, pemerintah kota dapat juga menggunakan indikator SDG 11 sebagai alat refleksi dan navigasi pembangunan. Beberapa indikator kunci yang bisa menjadi tolak ukur utama kemajuan kota antara lain, proporsi penduduk yang tinggal di permukiman tidak layak, proporsi limbah kota yang dikelola secara aman, akses terhadap ruang publik hijau yang aman dan inklusif, serta tingkat kerugian akibat bencana di permukiman padat dan informal. Infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut hak asasi warga kota atas tempat tinggal yang bermartabat.
Sementara itu, kota-kota di negara lain mulai mengintegrasikan indikator SDG 11 sebagai alat ukur utama dalam menentukan keberhasilan tata kota. Di Seoul, misalnya, indikator seperti akses transportasi umum yang inklusif, ruang hijau per kapita, dan kualitas udara sudah menjadi dasar dalam setiap laporan capaian pembangunan daerah. Kota-kota seperti Curitiba, Medellín, dan Kopenhagen bahkan menjadikan transformasi permukiman informal sebagai strategi utama pembangunan.
Jepang menjadi salah satu contoh penting yang patut dicermati, bukan hanya dari kota-kota besar seperti Yokohama atau Kyoto, tetapi juga dari kota-kota kecil yang berhasil menerapkan prinsip keberlanjutan secara nyata. Kota Toyama, misalnya, dikenal sebagai pionir kota kompak (compact city) yang memperkuat infrastruktur permukiman terintegrasi dengan transportasi publik dan jalur pedestrian, sambil mengendalikan ekspansi lahan agar efisien secara energi dan biaya.
Di kota kecil Fujisawa, dikembangkan proyek Fujisawa Sustainable Smart Town, sebuah kawasan perumahan yang menggunakan 100 persen energi terbarukan, sistem pengolahan limbah cerdas, dan penerapan teknologi smart grid yang mendukung efisiensi penggunaan listrik di setiap rumah. Kota ini juga menerapkan prinsip passive design dalam arsitektur rumahnya, menciptakan ruang tinggal yang hemat energi tanpa mengandalkan teknologi mahal.
Higashi-Matsushima, kota kecil yang sempat luluh lantak akibat tsunami 2011, kini menjadi contoh adaptasi perubahan iklim dan ketahanan kawasan permukiman melalui pembangunan rumah tahan bencana, sistem energi lokal berbasis surya, serta jalur evakuasi yang terintegrasi dalam desain kota. Semuanya dibangun dengan melibatkan warga secara langsung dalam proses perencanaan.
3. Perlu memperkuat kebijakan yang tidak hanya berhenti pada visi besar

Infrastruktur dasar seperti sistem air minum yang langsung layak konsumsi, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga trotoar multifungsi yang mengintegrasikan drainase dan jaringan utilitas bawah tanah, menjadi praktik umum bahkan di kota-kota berpenduduk kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan bukanlah monopoli kota besar. Kemajuan suatu kota dapat ditumbuhkan dari komitmen, inovasi lokal, dan keberanian untuk menata ulang cara kita merancang permukiman.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kota-kota di Indonesia, termasuk di Lampung, perlu memperkuat kebijakan yang tidak hanya berhenti pada visi besar, tetapi juga disertai dengan petunjuk teknis yang detail dan implementatif sesuai kondisi di lapangan. Terlalu sering kita menjumpai program besar yang gagal menyentuh realitas karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika permukiman yang kompleks dan unik.
Selain itu, perencanaan partisipatif perlu dibebaskan dari sekadar seremoni. Partisipasi warga harus ditopang dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kontekstual yaitu melalui pemetaan partisipatif, forum warga, hingga pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan secara nyata. Bukan hanya konsultasi, tetapi benar-benar mendengarkan, memfasilitasi, dan merespon dimulai dari tahapan awal sampai ke akhir.
Kolaborasi lintas aktor juga sangat dibutuhkan dalam tahap implementasi. Bukan kolaborasi atas nama, tetapi yang berbasis pada data dan kajian ilmiah. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas harus duduk bersama dengan pemahaman yang sama bahwa kota bukan sekadar infrastruktur dan angka statistik, melainkan ruang hidup bersama yang harus dibangun dengan tanggung jawab kolektif.
Apa arti kota yang maju bila sebagian warganya masih tinggal di tepi sungai tanpa sanitasi, atau di lereng bukit rawan longsor tanpa perlindungan? Apa gunanya ekosistem inovasi digital bila tumpukan sampah masih menjadi pemandangan harian di sudut permukiman?
Sudah saatnya kita memaknai ulang kemajuan kota. Kota yang benar-benar maju bukan hanya yang mendapat skor indeks tinggi, tapi yang sudah selesai dengan urusan dasarnya. Kota yang memastikan setiap warganya punya tempat tinggal layak, akses air bersih, ruang terbuka, dan lingkungan yang aman dari bencana. Karena kemajuan sejati, sama seperti manusia, harus dimulai dari sandang, pangan, dan papan.
Dr.Eng. Fritz Akhmad Nuzir. S.T., M.A
Direktur Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center) Universitas Bandar Lampung dan Wakil Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Lampung